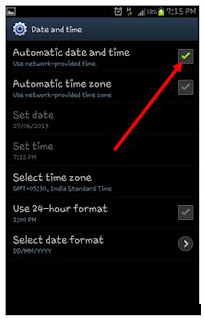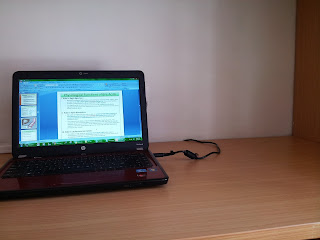Kasih Didendam, Rindu Dilempar
Selama hampir dua malam Nakhoda Tanggang dan anak kapalnya meredah lautan menuju Tanjung Kelana. Angin bertiup kencang dan sejuk, seakan-akan tidak mengalu-alukan kepulangannya ini. Namun, tekadnya untuk melihat semula wajah ibu-bapanya telah memberi kehangatan kepada tubuhnya untuk bertahan dari kesejukan itu. Tatkala matahari tegak di atas kepala pada hari kedua, bayangan pokok kelapa di pantai mula kelihatan. Lama kelamaan, kelibat orang ramai pula kelihatan. Tetapi, Nakhoda Tanggang dapat mengesan ada sesuatu yang tidak kena. Matanya sudah dilatih oleh arwah Nakhoda Awang untuk melihat setajam helang kelaparan.
Kalau dahulu pantai itu kurang kelibat manusia, kini, ia sudah mula bingit. Pada hemahnya, itu tidak mengapa. Apa yang menghairankannya, hampir semua anggota khalayak di situ memandang bahteranya; suatu pandangan yang tidak bersandarkan kekaguman; bukan pula seperti mahu menyambut kedatangannya. Mereka seolah-olah menyimpan sesuatu dari pengetahuannya. Sesuatu seperti kebusukan dendam. Tatkala bahtera Tanggang tinggal belasan depa untuk berlabuh, tiba-tiba seorang lelaki lingkungan akhir remaja berlari dari situ sambil menjerit dengan nada seperti ketakutan:
"N....Nakhoda! Itu bahtera Nakhoda Negeri Muara! Lari kalian semuaa!!"
Sejurus tamat saja kalimat itu diluahkan, maka bertempiaranlah lari sekaliannya, termasuklah lelaki tadi. Mereka yang berniaga meninggalkan perniagaan; baik penjual mahu pembeli. Yang menjala terkapai-kapai mendayung naik. Keadaan bertambah kecoh dan bingit. Puteri Aishah perasan akan suasana ini, lalu keluar dari kamarnya ke depan kapal. Dia juga tidak faham akan apa yang berlaku.
"Apakah gerangan yang terjadi, kanda. Mereka ini....mereka ini sepertinya gentar dengan kunjungan kita"
"Kanda juga bingung dinda. Ini kepulangan pertama kanda ke kampung halaman kanda ini. Entah apa yang sudah terjadi pada mereka semua ini.
"Oh, dinda rasa tidak sedap hati tentang ini kanda. Mungkinkah....."
"Dinda jangan risau. Bukankah ayahanda sudah menghantar anak kapal yang terbaik untuk membantu kita andai apa-apa terjadi nanti," Tanggang pantas memintas.
Perlahan-lahan bahtera Nakhoda berlabuh. Tempat itu sudah membisu; hanya deruan angin yang bersuara, memukul dedaunan kelapa.
"Apa-apa pun, kita turun dulu dari bahtera ini. Mari!," katanya sambil turun, lalu menghulurkan tangannya untuk membantu. Nakhoda Tanggang mengarahkan beberapa orang anak kapal turun sekali untuk berjaga-jaga.
Perlahan-lahan Nakhoda Tanggang memimpin laluan, langkah demi langkah menuju ke arah rumahnya yang berhampiran. Sudah sekian lama tidak menjejakkan kaki di bumi Tanjung Kelana ini, namun tiadalah dia lupa akan kampung halamannya. Setapak demi setapak, akhirnya dia tiba di sebuah kawasan, hanya ada sebatang pokok kelapa tanpa pohon, yakni dahulunya menjadi tempat pertemuan Nakhoda Awang dengan bapanya- saat bermulanya perpisahan Si Tanggang dengan keluarganya. Terataknya sudah dekat. Mereka melangkah lagi. Seketika kemudian, Nakhoda Tanggang mengesan sesuatu yang tidak kena.
Di sebalik tempat yang sepatutnya berdiri sebuah teratak usang, tersergamlah sebuah rumah, bukan........ Ianya laksana sebuah hasil senibina. Halamannya berpagar, berpengawal, asasnya daripada batu, dindingnya utuh, menjangkau kawasan yang luas. Ada pasu di sekelilingnya dan tangga untuk menuju ke pintu utama. Dia kebingungan. Apakah makna semuanya ini. Siapakah tuan kepada rumah yang serba agung ini? Apakah nasib yang menimpa keluarganya? Persoalan demi persoalan bertubi-tubi menghambat mindanya. Lalu bertanyalah dia:
"Wahai pengawal, bukankah suatu ketika di sini ada sebuah teratak usang? Maka apakah takdirnya ia, dan juga penghuninya, seorang pemuda dan dua orang tuanya?"
"Siapakah engkau wahai pemuda? Kalian bukan diam di negeri ini? Inilah kawasannya Datuk Temenggung, Penghulu bagi keselamatan seluas-luasnya tanah Tanjung Kelana ini."
Si Tanggang tersentak. Nama itu tidak pernah akan dilupakannya. Apakah itu kekandanya yang dimaksudkan?
"Temenggung katamu? Temenggung bin Talang??"
"Cis! Biadap sungguh adabmu wahai pemuda? Apa kamu ingat Datuk Temenggung itu keluarga kamu?? Berambus kalian semua dari sini!!"
Pengawal mula mengacu tombak. Ah, apatah lagi Nakhoda Tanggang. anak-anak buahnya lebih pantas menghidu suasana , lantas masing-masing mengorak langkah. Pergelutan berlaku. Suasana kecoh. Puteri Aishah menjauhkan diri, tapi tidak berkata apa-apa. Dua-dua belah sama handal, sama tangkas.
Seakan-akan pergelutan itu tiada penyudahnya, kedengaran suara seorang wanita, seorang yang agak tua, terketar-ketar nadanya dek marah, dari jendela di bilik yang tidak jauh dari situ. Pergelutan terhenti mendadak. Semua tergamam.
"Heiiiiiiiiii....Apakah gerangannya kalian pengawallllll. Bising macam ayam jantan hendak beranak! Kacau saja aku hendak lena ini. Siapakah yang datang membikin onar ini?"
"Maaf Bonda Deruma, ini cuma pendatang luar yang tersesat saja. Akan kami singkirkan sebentar lagi."
Nakhoda Tanggang sudah pasti sekarang. Ya, ianya bukan kebetulan, tapi satu kenyataan....
"Ibu! Apakah, ibu tidak kenal akan anak kandung ibu ini. Ini Si Tanggang ibu. Ingatkah ibu akan janji Tanggang dahulu untuk kembali ke sini semula walau susah bagaimana jua. Lihatlah sekarang, Tanggang sudah pulang ibu," nadanya sedih mendayu-dayu. Mana tidaknya, berpisah sudah berdekad lamanya.
Wanita tua itu terdiam seketika, kemudian berjalan menuju ke tangga pintu utama. Dia berhenti di situ, tidak turun, memerhatikan seorang demi seorang sehinggalah ke muka Nakhoda Tanggang akhirnya.
"Engkaukah Si Tanggang? Akhirnya kau pulang, ya! Si anak derhaka!! Tahukah kau betapa payahnya hidup aku menanti kepulangan kau. Ayahmu mendoakan keselamatanmu siang dan malam, hingga dia mati dalam sujudnya 5 tahun yang lepas, maka baru sekarang baru engkau hendak pulang? Bau secebis kertas buruk pun aku tidak terima tentang khabarmu di sana. Itu..... perempuan itu pasti isterimu. Lalu di mana hak aku sebagai ibu engkau untuk melihat majlis nikah kamu!? Lihat abangmu. Dialah contoh anak yang baik, semenjak dia dapat bekerja di bawah sultan, terus dia mengumpul harta, lalu membinakan aku satu singgahsana yang sungguh cantik ini. Kalau mengharapkan kau, memang sampai ke kubur pun belum tentu dapat!"
Tanggang ternganga mendengar itu semua, laksana dibuai mimpi. Apa semua ini? Hasratnya ingin meluahkan rindu tetapi, benci yang dilempar. Ayahnya sudah mati? Kenapa dia tidak mendapat khabar langsung tentang itu. Abangnya kini bekerja di bawah sultan?? Demi Tuhan, dia sanggup meninggalkan segala pangkat yang telah diterimanya untuk kembali pulang andainya dia mengetahui hal tersebut. Ya, tentang hal perkahwinannya itu, dia mendengar nasihat Nakhoda Awang agar tidak mendedahkan keluarganya pada bahaya. Namun, apakah ini harga pengorbanannya selama ini? Pengorbanannya,kesepiannya, rindunya demi membela nasib keluarga......
Tetapi Nakhoda Tanggang insan terdidik. Kata gurunya dahulu, andai orang membalingmu dengan batu, maka lemparkanlah buah baginya. Dia bersabar.
i....ibu. Maafkan Tanggang kerana tidak mengirimkan sebarang khabar. Ini semua pesan Nakhoda Awang dahulu agar.....
"Ah! Persetan dengan nakhoda Awang kau tu!" Tanggang dipintas. " Dalam sedekad selepas pemergian kau, barulah aku tahu bahawa dia seorang pembunuh. Ada orang melihat kelibat seorang berpakaian nakhoda di sekitar istana suatu ketika dahulu. Inipun abangmu yang menceritakannya padaku. Jikalau tidak, seumur hidupku akan tertipu dengan lagak baiknya itu".
Tanggang terketar-ketar sebak. Apa lagi...apa lagi yang mampu dikatakannya. Dia juga terkejut dengan pendedahan nakhoda Awang di saat akhir hayatnya di istana dahulu. Ibunya yang dahulunya kasih kini sudah lantang memaki hamunnnya. Air mata Nakhoda Tanggang berlinang perlahan-lahan. Suasana ketika itu senyap. Hanya mereka berdua yang bersuara.
"Apakah ibu tidak mahu menerima kepulangan Tanggang ini. Tahukah ibu betapa lamanya Tanggang nantikan saat kita semua dapat bersua kembali? ", tutur Tanggang perlahan.
"Sudahlah Tanggang, aku sudah meluat dengan rindu-rinduan engkau ini. Pergilah engkau semula balik ke negeri Muara sana. Aku sudah hidup gembira dengan kemewahan ini. Kedatanganmu hanya membuat aku lagi meluat saja."
Air matanya tidak dapat dibendung lagi. Bercucuran membasahi pipinya kini. Alangkah peritnya menanggung cacian dari ibu kandung sendiri.....
``Andai itu yang ibu mahukan, maka baiklah. Tanggang akan berlalu dari sini. Tapi, kirimkan salam Tanggang pada......
Tiba-tiba keadaan sekeliling menjadi riuh. Segerombolan manusia datang berkunjung ke singgahsana itu. Dari kelibat ramai, muncul seorang pemuda menjerit. Ibu!, Ibu! Saya sudah......Nadanya tersekat tatkala dia terpandang kelibat Tanggang berhampiran pagar. Pakaian pemuda ini berkilat, laksana kerabat diraja. Tangannya memutarkan gelang kekunci, sambil berjalan menghampiri Tanggang dengan langkah yang penuh angkuh.
Ha! Itu pun kau Temenggung. Tengoklah adikmu ini; mahu pulang setelah sekian lama dibiarkannya kita ini. Tak tahu malu sungguh.
``Jadi, aku memang tak silap, engkau ini memang adikku dahulu. Aku ingatkan pelanduk dua serupa saja".
Tanggang mengesat air matanya. "Abang, bagaimanakah abang dapat berkhidmat di bawah sultan? Mengapa tidak dikhabarkan pada Tanggang.
"Hahahaha.....panjang ceritanya wahai adikku. Beginilah, biar aku pendekkan. Sejak peristiwa engkau merampas peluang aku untuk berkhidmat di bawah sultan dahulu, aku tekad belajar ilmu mempertahankan diri. Tapi, aku tiada berguru. Dengan pohon kelapa saja aku berlatih. Jadi, entah bagaimana, ketika aku hendak mencari kayu api di hutan, aku berjaya menyelamatkan seorang budak perempuan yang sedang melarikan diri dari seekor harimau. Budak itu merupakan anak perempuan sultan, lalu sejak hari itu aku berkhidmat dibawah baginda.
"Agaknya Sultan kagum dengan kepakaran aku, yang berjaya menumpaskan semua lanun dan keparat yang cuba membuat onar di sini. Maka namaku dijadikan nama kedua tertinggi selepas Datuk Bendahara. Ya, sebelum aku terlupa. Gurumu itu, Nakhoda Awang merupakan orangnya yang bertanggungjawab membunuh ayahanda kepada baginda sultan kini. Maka engkau sebagai anak buahnya, akan kupenjarakan kerana kesalahan bersubahat. Pengawal, tangkap mereka semua ini!!
Sejurus saja tamat arahan Datuk temenggung, para pengawal dan pengikutnya cuba memberkas pengikut Nakhoda Tanggang. Sekali lagi pergelutan tercetus. Namun, orangnya Tanggang sudahpun keletihan, bahkan bilangan mereka jauh lebih kecil. Semuanya tertangkap, termasuk Tanggang. Si Temenggung menarik rambut adiknya, lalu membisikkan sesuatu:
"Kalau kau nak tahu, dahulu ibu ada cuba mengirim surat pada engkau, untuk mengkhabarkan tentang kematian ayah. Tapi, maafkan aku kerana tidak mengirimkannya. Aku malas.....". Bawa mereka semua ke istana, seru si Temenggung pada konco-konconya.
Air wajah Tanggang berubah. Airmatanya yang tadi deras mengalir, kini kering dek bahang kemarahan. Dia tidak dapat lagi menerima semua hakikat ini. Rupa-rupanya selama ini, dia menanti akan sesuatu yang tidak wujud- kasih sayang keluarga. Fikiran Tanggang mula berkecamuk. Dia rasa dikhianati. Dia rasa, seperti sudah tiada sesiapa lagi di dunia ini yang memerlukannya. Dia sudah faham mengapa khalayak ramai bertempiaran lari melihat bahteranya. Semua orang di sini takut akan si Nakhoda Negeri Muara.
"Maafkan kanda wahai Puteri Aishah," tuturnya dalam hati............
Dengan ketangkasan sepantas harimau, Si Tanggang menyiku perut pengawal yang memberkasnya-kiri dan kanan. Semua orang tersentak. Tanggang tangkas melarikan diri menuju bahteranya, meninggalkan pengikutnya meronta-ronta, dan yang lebih penting-isterinya yang sedang hamil itu. Puteri Aishah terduduk lemah. Dia tidak mampu bersangka baik di saat ini. Dia hanya mampu menangis melihatkan kekandanya melarikan diri seorang diri, tanpanya di sisi.
Si Tanggang berlari sekuat hati menuju bahteranya. Betapa ramai pengikut Temenggung mengejarnya. Dia memberikan isyarat supaya anak kapal yang tinggal melepaskan tali yang menambat kapal. Maka sesampainya di pelabuhan, dilompatnya akan perhentian itu; cukup-cukup saja sebelah kakinya masuk ke badan kapal yang sedang berlayar itu. Anak anak kapalnya bingung.
"Apakah yang telah terjadi Nakhoda? Mana Puteri? Aishah"
"Mereka semua sudah tertangkap. Burung utusan kita juga. Mujur saya dapat melarikan diri. Keadaan sudah tidak selamat; benar kata-kata nakhoda Awang. Ayuh, kita pulang meminta bantuan.
Nakhoda Tanggang bangkit memandang pantai Tanjung Kelana dengan nafas yang tercungap-cungap. Dia memerhatikan kekandanya yang seakan-akan menyesal kerana tidak membakar kapalnya terlebih dahulu. Bakar? Barulah dia teringat akan mimpinya dahulu. Ia benar-benar terjadi. Isterinya kini sudah tiada. Lebih separuh anak kapalnya sudah ditangkap. Hakikatnya, bahteranya seakan-akan sudah "dibakar".
Nakhoda Tanggang tahu bahawa waktu ini tidak sesuai untuk berlayar. Matahari tidak kelihatan. Awan gelap. Angin sudah mula meniup. Ombak sudah mula menghayun. Masakan tidak, waktu sudah menjelang malam. Dia tahu, hujan akan turun dalam separuh jam lagi, tetapi bersama-sama guruh dan petir. Kali terakhir dia meredah petir adalah bersama-sama Nakhoda Awang. Suasana ketika itu begitu sejuk, sehingga dia demam beberapa hari selepas tamat berlayar.
Kini, dia keseorangan. Sudahlah perasaan hatinya bercampur-baur- marah, sedih, risau, gentar; semuanya berlaku sesingkat satu hari. Fikirannya mula menguasai diri. Dia sudah terbayangkan riak wajah sultan tatkala mengetahui puterinya tersadai di tanah orang. Dia sudah terbayang wajah-wajah rakyat Negeri Muara yang mengutuknya nakhoda tidak bertanggungjawab. Dia sudah terbayang darjah kebesarannya dilucutkan, dan dia kembali hidup dalam teratak. Tanpa disedarinya, hujan sudah mula turun. Ah! Alangkah bagusnya jika dia tidak perlu melalui semua ini. Alangkah bagusnya jika nyawanya ditarik sekarang........
Sesaat selepas itu terdetik di hatinya, petir yang sangat terang memancar kearah bahteranya, lalu menyambar layar kapal yang sudah basah. Ia patah, lalu jatuh menjunam ke dalam laut. Suasana sekeliling begitu gelap, dan hujan sudah mula turun menyimbah. Gelora ombak seakan-akan gembira memukul kapalnya, yang kini terpusing-pusing tanpa hala tuju. Maka dalam huru-hara itu jugalah, bahteranya terhempas sebuah batuan yang sangat besar. Segelintir anak kapalnya tercampak keluar, ada juga yang terhentak ke batu lalu tidak sedarkan diri. Nakhoda Tanggang berpaut pada sisa tiang layar yang tinggal, cuba untuk bertahan dari gelora ombak.
Namun, dia sudah tahu kesudahan nasibnya. Dialah Si Nakhoda, kemahiran ilmunya tentang samudera tiadalah dapat dijilidkan dengan sebotol dakwat pena. Dia dapat merasakan air yang seakan-akan surut seketika, tiba-tiba ombak berhenti bergelora. Maka kemudian, dari sejauh pandangan matanya memandang, ombak besar, setinggi 3 bahtera tersusun yang sudah dijangkanya meluru pantas kearah sisa bahteranya. Bunyinya semakin kuat. Ia semakin dekat. Peluhnya menitis dalam hujan. Dia hanya mampu memejamkan mata......
Satu hentaman yang sangat dahsyat berlaku. Bahteranya bersepai punah lalu tersadai ke kawasan cetek. Anak-anak kapalnya entah ke mana. Nakhoda Tanggang masih bernyawa; dia tertelangkup ke batu-batuan. Tubuhnya terasa sakit, darah mengalir keluar tidak henti-henti. Seakan-akan tahu ajalnya sudah tiba, dia menguatkan kudrat terakhirnya, cuba sujud meminta keampunan, atas kesilapannya, atas tanggungjawabnya yang tidak tertunai, jua atas kejahilan dan kenaifannya
"Ampunkan patik wahai baginda sultan.......
"Ampunkan kanda wahai dinda........
"Maafkan Tanggang mak, ayah........
"Maafkan saya wahai penduduk negeri Muara.......
"Ampunkan aku, ya Allah......"
...................................................................................................................................................................
Maka tatkala genap sepurnama berakhir, tapi tiada terlihat oleh baginda sultan akan kelibat puteri dan nakhodanya, maka maklumlah baginda akan takdir kedua-duanya. Lalu dihantarnya bala tentera seberat beratnya menuju ke Tanjung Kelana, maka tercetuslah peperangan antara dua wilayah ini.
Adapun isterinya Tanggang dan pengikutnya; mereka semua dibunuh bersama-sama dengan tawanan perang lain. Tiada siapa tahu akan bila peperangan ini terhenti. Apa yang tinggal kini hanyalah cerita. Cerita warisan dari mulutnya Si Temenggung. Sebarnya, Si Tanggang itu adalah anak derhaka kerana tidak kembali menjenguk ibunya pulang selepas lalai dengan kemewahan harta dan pangkat selepas berkhidmat di bawah sultan. Adapun manusia ini sikapnya menokok tambah, maka jadilah ceritera Si Tanggang itu laksana hari ini yang didengar setelah turun temurun disebar.
Bagi nasib Si Tanggang pula, dengan kehendak Allah, maka jasadnya tiadalah dimamah bumi, maka kekallah dia sujud di batu-batuan hingga ke hari ini. Ada yang kasihan, tidak kurang juga yang mengutuk dan mengejinya. Andainya Si Tanggang masih hidup untuk menceritakan kisahnya yang sebenar pada manusia kini.........
~TAMAT~
By- RUSYDI MZ